Koran Tempo, 13 September 2009
Afthonul Afif, Alumnus Psikologi Klinis Pascasarjana UGM Yogyakarta
Dalam perspektif awam, imajinasi masih sering diposisikan dalam arti peyoratifnya. Imajinasi dianggap serupa dengan ilusi, khayalan, dan fantasi. Salah persepsi ini berakibat pada masih kurang dipertimbangkannya imajinasi sebagai sumber pengetahuan yang sahih.
Orang sering mengajak kita untuk berpikir realistis ketika kita mengajukan gagasan yang muluk-muluk. Mereka tidak menyadari bahwa anjuran mereka –sebagaimana dikemukakan Allan Loy McGinnis dalam buku best seller-nya, The Power of Optimism (1993) sebenarnya bentuk kekhawatiran-kekhawatiran yang disembunyikan. “Worry is misuse of imagination” (kekhawatiran adalah imajinasi yang disalahgunakan). Kekhawatiran itu, oleh Kierkegaard dianggap sebagai sikap yang berlebihan dalam merespon bahaya, atau semacam sikap memandang rendah kemampuan kita.
Mengganggap imajinasi sejenis dengan khayalan, fantasi, atau ilusi, merupakan sikap yang gegabah. Istilah fantasi itu sendiri lebih berkaitan dengan daya membayangkan sesuatu hal yang tidak real atau yang tidak mungkin terjadi. Dengan demikian, fantasi sepadan dengan khayalan atau ilusi, terjemahan dari bahasa Inggris, illusion. Secara terminologis, ilusi berarti ide, keyakinan, atau kesan tentang sesuatu yang jelas-jelas keliru. Jika fantasi (daya yang menghasilkan khayalan) berhubungan dengan gambaran objek yang tidak mungkin dan memang tidak ada dalam kenyataan, maka imajinasi merupakan daya yang menghasilkan gambaran objek yang bersifat mungkin atau logis. Imajinasi tidak terkait dengan penggambaran yang membabi buta tentang suatu objek atau konsep tertentu.
Dalam bahasa inggris, ada beberapa variasi kata untuk imajinasi, yaitu imagery, imaginary, dan imagine. Imagery merupakan bahasa figuratif untuk merujuk sebuah gambaran, objek, ide, dalam pikiran seseorang (pembaca atau pendengar), sehingga istilah ini sering digunakan oleh para penyair dalam karya-karyanya. Imagery sering diartikan sebagai perumpamaan/tamsil, meskipun ia memiliki arti yang lebih luas dari sekedar perumpamaan. Selanjutnya, imaginary dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai yang imajiner atau khayal; contohnya bilangan imajiner sebagai bilangan khayal. Sementara kata imagine (kata kerja) berarti membentuk suatu gambaran mental tentang sesuatu, atau memikirkan sesuatu sebagai bisa terjadi atau mungkin. Imagine adalah tindakan membayangkan, meskipun pada prakteknya terdapat perbedaan antara “membayangkan” dan “mengimajinasikan”.
“Membayangkan” mempunyai konotasi sebagai sesuatu yang lebih mudah dilakukan karena berhubungan dengan sesuatu yang menyenangkan. Sedangkan “mengimajinasikan” itu merambah wilayah yang lebih luas sehingga tidak dapat direduksi sebagai sekedar membayangkan. Maka dari itu, imajinasi lebih tepat diartikan sebagai kekuatan potensial yang telah memberikan kontribusi berharga bagi lahirnya pengetahuan.
***
Perlu diketahui perbedaan antara berimajinasi dan berpikir (logis), lebih khusus terkait dengan proses lahirnya pengetahuan. Berpikir merupakan aktivitas mental untuk melahirkan atau memformulasikan pengetahuan dengan merujuk pada aturan berpikir atau konsep tertentu yang cenderung bersifat membatasi, bahkan mengikat. Misalnya anjuran berpikir lurus menurut logika identitas Aristotelian –di mana cara berpikir yang tidak mematuhi hukum logika tersebut dapat terjatuh dalam “sesat pikir” (the fallacy). Sementara dalam berimajinasi proses mental kita tidak lagi diikat oleh hukum berpikir atau konsep kebenaran tertentu, sehingga pikiran menjadi bebas untuk mencari wawasan pengetahuan baru.
Disadari atau tidak, peran imajinasi begitu besar dalam melahirkan teori-teori agung di bidang ilmu pengetahuan. Ketika para ilmuwan sudah kehabisan ide untuk memecahkan suatu permasalahan—karena logika telah menunjukkan keterbatasan-keterbatasannya, terkadang imajinasi bebas mereka justru yang mempunyai peranan besar dalam pemecahan problem-problem keilmuan. Bahkan ilmuwan sekaliber Einstein mengatakan, ”imajinasi lebih penting daripada pengetahuan”.
Peran imajinasi dalam proses penelusuran pengetahuan membawa banyak hal yang sering tak terduga. Meski berimajinasi tidak dibatasi oleh hukum berpikir dan konsep tertentu, namun proses mental tetap terarah pada citra atau imaji-imaji tertentu sebagai representasi dari persoalan yang sedang dibayangkan. Ketika Einstein menemukan rumus E=mc2 , dia tentu meng-imaji-kan variabel-variabel itu dalam pikirannya. Ketika Newton tiba-tiba menyadari teori gravitasinya karena melihat buah apel jatuh ke tanah, dia juga men-citra-kan sesuatu dalam benaknya. Dengan demikian, mengimajinasikan “imaji” merupakan proses yang melahirkan kedua teori tersebut.
Tentang kemampun melahirkan konsep dari imaji-imaji yang dicecap, ada sebuah konsep menarik yang diperkenalkan Sartre dalam bukunya L’imaginaire: Psychologie phenomenogique de l’imagination (1940), yaitu tentang “imajinasi kreatif”. Imajinasi kreatif ini terkait dengan kemampuan pikiran seseorang untuk merasakan apa yang disebut Kant “pengalaman estetik”. Ketika seseorang mampu menangkap makna dan menemukan seepisode cerita dalam sebuah lukisan, atau merasakan emosi dalam selantun lagu yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain, maka orang itu memiliki imajinasi kreatif. Dengan kata lain, tidaklah disebut imajinatif jika melihat makna dan cerita dalam sebuah lukisan yang juga bisa dilihat orang lain. Imajinasi kreatif ini disebut Sartre sebagai “tindakan menciptakan sebuah objek dalam ketiadaannya”.
***
Hans George Gadamer, dalam Philosophical Hermeneutics (1977) mengatakan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang tumbuh dalam ruang sosial dan masa historis tertentu. Citra tentang manusia dan lingkungannya selalu dibentuk dan direkayasa dalam lembaran sejarah. Sehingga, tidaklah berlebihan jika Simone Weil menganggap bahwa imajinasi dan fiksi telah membentuk lebih dari tiga perempat kehidupan nyata manusia.
Pernyataan di atas hendak menegaskan bahwa pengetahuan yang kita peroleh sebenarnya lahir dari imaji-imaji tentang segala hal yang telah kita cecap, entah ia merujuk pada objek yang real ataupun yang imajiner. Imaji-imaji yang memenuhi ruang mental kita itu menjadi semacam penyedia bahan baku bagi kegiatan merumuskan pengetahuan.
Dalam konteks ini, antara imajinasi dan rasio sebenarnya saling mendukung. Sebagai salah satu potensi intelek, imajinasi berfungsi sebagai pemecah kebuntuan ketika rasio tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan pengetahuan yang membekap kita. Dengan dayanya, imajinasi mampu membuat tautologi-tautologi baru atas imaji-imaji yang memenuhi benak kita yang tidak dapat dikerjakan oleh rasio. Ketika pola-pola tautologi itu telah eksis dalam pikiran kita, rasio kemudian memerankan dirinya kembali, yaitu sebagai evaluator dan perumus bagi tautologi-tautologi itu agar polanya semakin matang dan presisi. Imajinasi membuat dunia hadir dalam banyak kemungkinan, dan rasio membuat kemungkinan-kemungkinan itu menjadi pengetahuan yang masuk akal.
Imajinasi juga memampukan kita menghayati dunia dan kenyataan sebagai momen puitis (ingat imajinasi kreatifnya Sartre). Jika di ranah saintifik antara imajinasi dan rasio masih bisa didamaikan, maka di ranah estetis keduanya cenderung saling menegasikan. Sebagai modus representasi dunia dan kenyataan, imajinasi adalah sumber bagi bahasa konotatif-puitis, sementara rasio adalah sumber bagi bahasa denotatif-logis. Kedua modus representasi ini akan melahirkan corak dunia yang sangat berbeda.
Jika kita hanya mengandalkan bahasa denotatif-logis sebagai basis representasi, maka dunia akan mewujud sebagai objek formulatif semata. Di ranah estetis, dengan mengacu Heidegger, bahasa konotatif-puitis sebenarnya lebih berpotensi memunculkan “ketidaktersembunyian” (aletheia) karena lebih membuka pengalaman, bukan menciutkannya. Oleh karena bahasa puisi hendak meng-imaji-kan sesuatu, maka hanya imajinasilah yang mampu memberikan konteks imajinatif pada pikiran kita.


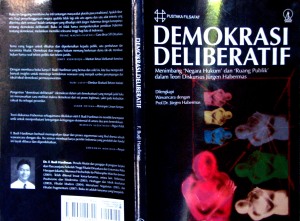

 Koran Tempo, 14 Juni 2009
Koran Tempo, 14 Juni 2009 Koran Tempo, Minggu 17 Mei 2009
Koran Tempo, Minggu 17 Mei 2009 Kompas, Sabtu 16 Mei 2009
Kompas, Sabtu 16 Mei 2009 Afthonul Afif,
Afthonul Afif, 
 Kompas, Sabtu, 27 Desember 2008
Kompas, Sabtu, 27 Desember 2008


Recent Comments